Depresi
.jpg)
Ward in the Hospital in Arles 1889 by Vincent Van Gogh.
Sewaktu kecil, Dedi memberi tahu gurunya bahwa dia diadopsi.
Semasa remaja, dia menangis tersedu-sedu, sedih tak terkira karena ‘teman baik’nya pindah ke luar kota. Dia tak punya teman—baik atau tidak baik.
Pada usia sembilan belas, Dedi tenggelam dalam kesedihan yang dalam. Dia berbaring di tempat tidur siang dan malam, meratapi kemiskinan yang ada dalam khayalnya. Kami punya empat mobil keluaran tahun sebelumnya dengan nomor polisi satu digit—dua ganjil dan satu genap , tiga pembantu, tukang kebun, supir dan seminggu sekali kolam renang di belakang rumah dibersihkan oleh pembersih kolam profesional. Rumah yang pajak bumi dan bangunannya bisa untuk membeli tunai sebuah rumah tipe 72 m2 di pinggiran kota.
Tidak ada psikolog atau psikiater yang bisa menyembuhkan depresi yang disebabkan oleh imajinasi yang cacat.
Kuakui bahwa istriku memanjakannya secara berlebihan. Uang bukan persoalan bagi kami, tapi dua kali terdaftar di jurusan dan perguruan tinggi yang berbeda tanpa pernah sekalipun menginjak ruang kuliah membuatku kesal. Untung aku berhasil membujuknya untuk mendaftar di fakultas sastra sebuah universitas swasta.
Kini di awal dua puluhan, jika tidak ke kampus, maka dia akan diam di rumah membaca novel atau bengong menatap kolam ikan koi.
Pernah ketika Jumat sore sepulang kerja, aku menemukannya sedang makan semangkuk mi instan di depan televisi ruang keluarga.
"Bagaimana kuliahmu?" tanyaku.
Dia menyorong selembar kertas ke arahku. Huruf "A+" dan kata "Luar Biasa!" ditulis dengan spidol merah.
"Papa takkan mau membacanya," katanya, nadanya datar. "Tentang keluarga asli dan temanku yang hilang."
Aku dan istriku telah berhenti berdebat dengannya bertahun-tahun lalu—dengan suara serak meyakinkannya bahwa kami adalah orang tua kandungnya, bahwa ingatannya palsu, bahwa dia tidak miskin dan tidak ada teman yang pernah meninggalkannya.
"Menulis baik untukmu, Nak," kataku.
Dengan lembut dia berdeham.
"Mestinya begitu."
"Papa ingin membacanya."
Dia hanya mengedikkan bahu, bangkit perlahan dari sofa, dan meletakkan mangkuk kosongnya ke dalam mesin pencuci piring.
"Mamamu dan aku berencana menemui Eyang Putri besok di rumah sakit," kataku. "Menurut dokter, waktunya tak lama lagi. Maukah kamu ikut dengan kami?”
"Eyang Putri? Mengapa? Aku belum pernah menjenguknya."
"Nanti kamu takkan punya kesempatan lagi."
"Maksudku, aku bahkan tidak mengenalnya."
"Eyang Putri sekarat," kataku.
Mata Dedi berkedip-kedip, pertanda emosinya muncul ke permukaan.
"Jika kita menunda membesuknya, mungkin kita hanya akan menemui jenazahnya."
"Makanya Papa minta kamu ikut menemani kami."
Dia menatapku dengan tatapan penuh kasihan kepada orang asing yang membutuhkan perhatian.
"Ya, tentu saja."
"Kamu tidak punya kegiatan akhir pekan?"
Dia menghembuskan napas panjang karena pertanyaanku yang tidak masuk logika.
"Baiklah," kataku, "Papa mau mandi. Kamu sudah bilang mamamu apa yang kamu inginkan untuk makan malam?"
"Tidak."
Aku membaca makalahnya, dan berpikir akan tertidur pada alinea kedua atau ketiga. Ternyata tidak.
Sebagai gantinya, aku menambah terang lampu baca di samping ranjang untuk mendapatkan cahaya yang lebih baik. Sejak kecil, Dedi telah menyampaikan delusinya, tapi tidak pernah dengan realisme seperti ini, dan tidak pernah dengan perspektif yang rasional.
Judulnya, ‘Hidupku yang Bahagia’
Dedi menulis tentang memiliki seorang istri dan anak-anak, karir yang cemerlang sebagai seorang novelis yang mendapat pujian dari para kritikus, keseriusannya dalam melakukan riset dan menyusun plot, kepuasan dalam pergaulan sosial, dan tujuannya untuk berbagi kebahagian dan pengetahuan dengan orang lain.
Namun, paragraf akhir dari esai itu berbunyi:
"Belakangan ini saya menyadari bahwa kenangan itu ada hanya di pikiran saya, tertanam di bawah sadar selamanya, seolah-olah seorang ahli hipnotis menanamkannya untuk menyiksa saya. Artinya, sesungguhnya saya belum pernah merasakan bahagia, kecuali rasa sakit karena perpisahan dengan orang-orang yang saya cintai. Harapan saya, suatu hari nanti rasa sakit ini akan hilang bersama datangnya cinta sejati."
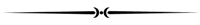
Setelah mengarungi kemacetan lalu lintas yang parah selama hampir dua jam, akhirnya kami tiba juga di rumah sakit. Ibu mertuaku bersandar di bantal, matanya setengah terbuka dan napasnya satu-satu.
Setelah diam beberapa menit, dia berkata, "Senang ... kalian ... datang."
Istriku bercerita padanya tak putus-putus, seakan mertuaku mengerti setiap kata-katanya.
Antara tidur dan terjaga, dia tampak menikmati kehadiran kami—terutama Dedi, yang duduk di sampingnya.
Ketika aku menyebutkan makalahnya, ibu mertuaku berkata:
"Bacakan ... untukku."
Istriku menjawab, "Maaf, Ma, kami tidak—"
Tapi Dedi mengeluarkan salinan makalahnya dari sakunya.
Saat Dedi membacakan esainya, energi kehidupan seakan mengalir ke dalam raga mertuaku, semangatnya mekar bagai kembang wijayakusuma bersemi di malam hari.
Ketika Dedi selesai membacakan paragraf terakhir, mertuaku berkata:
"Eyang ingat cerita itu ... Eyang pernah melihatnya sebelumnya."
"Apa yang Eyang pernah lihat?" tanya Dedi.
Tangan keriput meraba-raba sampai menemukan jemari Dedi.
"Dedi?"
"Iya, Eyang."
"Cucuku sayang, itu adalah anugerah. Pengalaman dan orang-orang yang kamu sangka hilang itu sesungguhnya belum datang kepadamu. Ingatanmu bukanlah kenangan, tapi visi dari masa depan. Eyang juga mengalami hal yang sama."
"Maksud Eyang kita berdua cenayang?"
Mertuaku mengangguk pelan.
"Sampai Eyang memutuskan untuk menerima kehilangan orang-orang dari masa depan Eyang, nyata atau tidak, Eyang tidak akan bersyukur untuk saat ini ... untuk orang-orang yang hadir dalam kehidupan Eyang sekarang, mencegah datangnya masa depan yang menyenangkan. Terimalah apa yang hilang, Sayang ... bahkan kehilangan diri sendiri ... dengan memberi dan menerima cinta orang-orang di sekitar kita."
Mertuaku kembali terdiam hanyut setengah sadar, untuk akhirnya berkata:
"Seandainya saja Eyang bertemu denganmu dulu, Eyang bisa memberitahumu sebelum ini. Tapi, Eyang senang ... kalian datang .... "
Dedi menatap mertuaku, matanya berkedip-kedip cepat. Aku mencoba memikirkan kata-kata yang sedang berkecamuk dalam dirinya yang mungkin menyusun kembali keping kehidupannya yang hilang.
Dia kemudian merengkuh aku dan istriku ke dalam pelukannya, menangis tanpa malu-malu. Air mata kami masih mengalir saat napas mertuaku terhenti. Dadanya diam tak lagi bergerak naik turun. Wajahnya teduh, tertidur dalam keabadian.
Kami terdiam hening, sampai kuputuskan untuk memecahkan kesunyian dengan kata-kata:
"Dedi, tolong panggil perawat, Nak.”
Dedi menyeka air mata dari wajahnya dan pergi.
Aku bertanya pada istriku:
"Apa benar keluargamu punya kemampuan meramal masa depan?"
Dia menggenggam tangan mertuaku dan mendesah:
"Aku tak yakin. Buktinya aku tidak memilikinya."
Aku melangkah ke luar menyusuri selasar. Kulihat Dedi sedang bersandar di konter ruang jaga.
Semenit kemudian dia kembali, seulas senyum tersungging di wajahnya.
"Perawat akan segera datang," katanya.
Kembali sunyi, sampai Dedi berkata:
"Mama tahu nama perawat yang bertugas? Yang rambutnya coklat keemasan lurus sebahu?"
"Maryam," jawab istriku. "Dia cantik, bukan?"
"Sepertinya aku pernah melihatnya."
"Dia menyukai sastra," kata istriku.
Mata Dedi berkedip cepat. Di antara isak tangis dan gelak tawa, dengan suara serak dia menjawab:
"Aku tahu."
Bandung, 17 Maret 2018