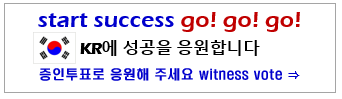REMBANG MERADANG

Masih dan akan terus terjadi kisah penguasaan kaum modal atas tanah milik petani di seluruh Indonesia, negara yang tak henti berbangga menyebut dirinya “Agraris”.
Salah satunya tentang tanah Rembang. Tentang rakyat di sana yang sedang melawan PT Semen Indonesia (PT. SI). Korporasi ini hendak mendirikan pabrik semen di tanah milik para petani. Pemodal ini sepertinya tak hanya salah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), tapi juga salah memilih “lawan”. Rembang dan sekitarnya adalah wilayah di mana sejarah perlawanan kaum tani telah menjadi semacam tradisi.
Bermula dari seorang Samin Surosentiko (1859 – 1914) yang mengajarkan sebuah laku spiritual berdasarkan pada nilai kejujuran dan semangat kebersamaan. Berpijak dari falsafah itu, Samin Surosentiko menggerakkan perlawanan petani melawan kolonial Belanda. Gerakan perlawanan kaum tani yang dipimpinnya ini lebih tepat disebut sebagai sebuah perlawanan sunyi, sebab tak ada senjata yang berbicara, tak ada kekerasan berperan. Yang ada adalah pembangkangan sipil dengan cara menolak tanam paksa dan menanam secukupnya tanaman sesuai kebutuhan hidup sendiri, tidak mau membayar pajak dan tak mau mengikuti aturan dari penguasa Belanda. Gerakan ini dilakukan dengan cara khas yaitu dengan bersikap lucu, berlagak bodoh, atau berpura-pura gila. Orang lucu hanya pantas ditertawai, orang bodoh hanya bisa dimaklumi, dan orang gila bebas dari hukum. Ketiga jenis orang ini dianggap tak berbahaya tetapi amat merepotkan. Kerepotan ini yang membuat Samin Surosentiko akhirnya dibuang ke Sawah Lunto, Sumatera dan meninggal di sana.
Yang juga menarik adalah ajaran Samin Surosentiko atau Saminisme ini banyak memiliki kesamaan dengan Anarkisme. Sifat-sifat perlawanan yang telah saya sebut tadi mirip dengan konsep revolusi ala Proudhon, seorang pemikir penting dalam Anarkisme. ‘Revolusi’ bagi Proudhon bukan berarti konflik kekerasan ataupun perang saudara, melainkan transformasi masyarakat yang bersifat perubahan moral dan menuntut etika tinggi para pelakunya. Dan perlawanan semacam inilah yang saat ini terjadi di Rembang. Para aktivis menggunakan simbol-simbol perlawanan dengan cerdas. Kecerdasan itu misalnya ketika justru ibu-ibu Rembang yang menjadi garda depan melawan PT. SI untuk dilekatkan dengan cerita rakyat tentang Ibu Bumi yang melawan Angkara. Atau dengan tinggal di tenda, di areal yang diaku PT. SI. Mereka sudah lebih dari 500 hari tinggal di tenda tanpa penerangan dan air untuk menunjukkan bahwa mereka adalah rakyat yang tahan uji. Protes mereka juga mendapat simpati dan dukungan dari para pegiat lingkungan dan aktivis HAM di luar Rembang. Solidaritasnya juga berupa perlawanan simbol, yang menghindarkan diri dari adanya kemungkinan konflik kekerasan. Bentuknya melalui berbagai gelar budaya seperti pentas musik, pameran senirupa, dan sebagainya.
Namun perlawanan budaya semacam ini juga memunculkan kritik bahkan dari kawan seperjuangan yang cenderung menganut konflik frontal. Tak boleh ada dialog dengan pencuri yang masuk rumah kita, tak ada waktu lagi untuk bermetafora, sebab perlawanan melalui simbol-simbol bakalan sia-sia dan saatnya dibutuhkan sebuah aksi nyata. Begitulah menurut mereka. Sebenarnya tak pernah ada yang bisa mengukur sebuah perjuangan demokratik disebut sukses ataukah gagal, sia-sia ataukah bernilai nyata. Demokratisasi adalah kata kerja, bukan sebuah hasil akhir, karena itu tak layak saling menilai. Kekerasan memang tak dianjurkan di jalan Proudhon dan Saminisme, meski demikian, Anarkisme tak memungkiri adanya pilihan tak popular itu. Pertempuran senjata dalam sejarah Anarkisme pernah terjadi yaitu ketika Bulan Juli 1936, José Buenaventura Durruti Dumange memimpin 3000 lebih anarkis bersenjata dalam perang sipil Spanyol melawan Fasisme. Namun juga jika yang dimaksud aksi nyata adalah jalan Durruti, maka kawan-kawan pengritik aksi budaya ibu-ibu Rembang juga hanya terlihat sebagai aktivis yang hanya besar mulut.
Maka kita jaga bara Rembang tetap meradang dalam melawan angkara. Suradira jayaningrat, lebur dening pangastuti!