Penulis Serius versus Selebritas Sastra

Anak kecil yang baru belajar karate, tiang listrik pun diajak berkelahi. Kata-kata ini sering saya lontarkan -- secara guyonan tentu saja -- merespon orang-orang yang senang memancing diskusi tak produktif di media sosial. Biasanya orang seperti ini baru belajar sesuatu. Lalu, ia asyik mengkritik atau menggurui sana-sini, termasuk memancing debat tak penting. Bahkan terkesan ia sedang mencari perhatian.
Ada orang yang merasa kritikus sastra, misalnya, tapi keliru menempatkan teori. Sering pula tafsirnya salah. Lain waktu ia kebingungan bagaimana menjelaskan kekuatan sebuah karya. Saking lucunya, ia sampai bilang: tidak ada kata-kata yang tepat untuk menggambarkannya. Lah, masa seorang kritikus tidak bisa menggambarkan dengan kata.
Tapi sudahlah. Lupakan. Biarlah ia bahagia dengan label kritikusnya dan merasa paling tahu sedunia. Lucunya, ada beberapa orang yang melayaninya. Sehingga ia makin keras kepala mendapat "lawan" orang-orang yang sesungguhnya jauh lebih pintar dari anak kecil ini. Ia pun makin menjadi-jadi. Padahal jika dibiarkan ia akan diam sendiri.
Ada lagi kisah lucu. Orang-orang yang baru belajar menulis, dan karyanya “dimuat” di Facebook dan beberapa antologi bersama, yang digarap secara gotong royong alias ia harus bayar untuk ikut serta. Mereka juga terjangkiti sindrom anak-anak anak-anak baru belajar beladiri: pamer jurus di mana-mana, selfie, dan seterusnya. Hebringlah.
Mereka juga suka ikut berbagai kegiatan sastra, di dalam negeri hingga negara tetangga. Kebutuhan mereka cuma sederhana: membangun eksistensi dengan hadir dan tampil di mana-mana. Sehingga bisa memperpanjang materi untuk biodata. Juga bisa posting foto-foto dan video di media sosial. Kualitas karyanya? Entahlah. Jangan tanya.
Menjadi selebritas dalam sastra itu jangan mudah ternyata. Tak perlu banyak membaca, tak perlu belajar sungguh-sungguh, tak perlu berdarah-darah menembus lubang jarum tembok seleksi media. Cukup tampil di banyak acara, haha-hihi di sana sini, membentuk perkawanan antar sesama mereka, lalu posting foto dan video di media sosial. Semudah itu.
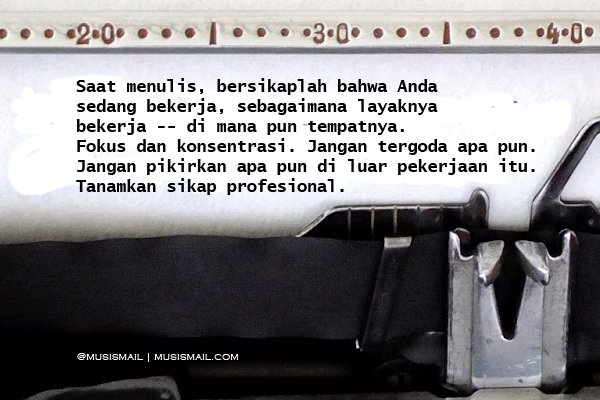
Urusan karya nomor dua, bahkan nomor dua puluh dua. Tidak penting-penting amat. Tak heran kita menemukan puisi-puisi "entah" di media sosial, panggung-panggung sastra, hingga berbagai antologi bersama – terutama antologi gotong royong yang mengutip bayaran tiap peserta. Juga antologi festival yang kuratorialnya dilonggarkan agar banyak perserta.
Dalam “jagad sastra hore-hore” semacam ini, perkawanan jadi faktor utama. Istilah “tak kenal maka tak sayang” sangat penting untuk “kesuksesan”. Tak heran, saya menemukan fakta dalam beberapa kurasi karya antologi bersama: puisi “entah” melenggang mulus, karya bagus tak lolos. Saya masih menyimpan beberapa puisi kawan penyair yang saya anggap pantas itu.
Ini fakta unik dalam sastra kita -- ketika karya tidak lagi menjadi panglima. Tapi apa boleh buat. Orang-orang yang suka berteriak tentang kualitas karya mungkin akan disebut sinting dan kurang kerjaan. Sebab buat mereka bersastra hanya buat kongkow dan hepi-hepi saja. Mereka bisa menulis kapan saja dan segera mempostingnya di akun media sosialnya.
Tentu penulis dan pegiat sastra serius -- yang menjadikan sastra sebagai ruang jelajah sekaligus belajar -- tak perlu galau. Semua adalah pilihan. Mau jadi sastrawan hore-hore, sekedar gaya atau penulis sastra yang tekun dan serius, silakan saja. Semua sah-sah saja. Meskipun sebaik-baiknya eksistensi ya karena karya, bukan karena gaya.
Depok, 31 Desember 2018 – 1 Januari 2019
MUSTAFA ISMAIL | IG: MOEISMAIL | @MUSISMAIL
Posted from my blog with SteemPress : http://musismail.com/penulis-serius-versus-selebritas-sastra/
Menarik ni kanda tulisannya.
Semoga cepat sadar bahwa sabut karatenya baru putih dan tiang tak patut diajak lawan
Posted using Partiko Android